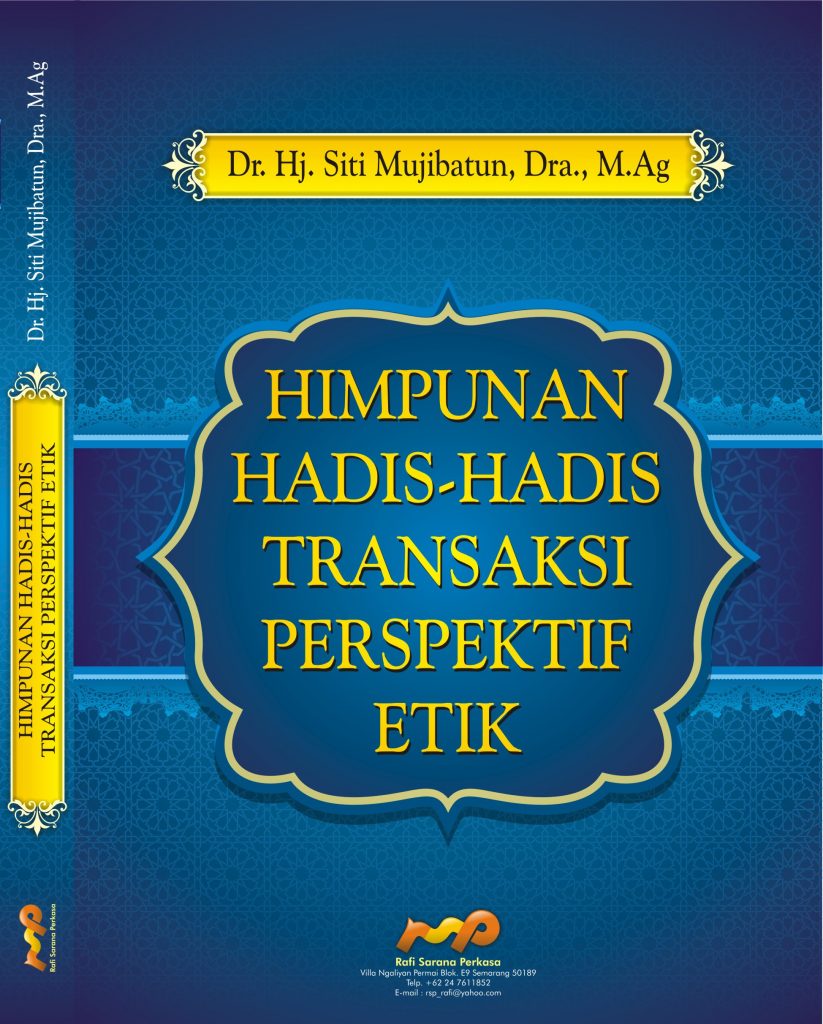
1. Definisi Transaksi
a. Pengertian transaksi menurut bahasa termasuk dalam bentuk akad secara umum. Sedangkan akad menurut bahasa adalah: ikatan dari dua ujung (tali), janji, jaminan.
b. Dari segi istilah: Para ahli hukum memberikan definisi transaksi (akad) dengan beberapa pengertian antara lain:
1). Hubungan perkataan salah satu dari dua pihak menurut Syara’, tampak adanya suatu akibat terhadap apa yang diucapkan tersebut pada obyeknya. (Madhkur, 1967: 534). Akibat yang terjadi dari hubungan perkataan oleh kedua pihak yang melakukan akad (‘aqidain) adalah melaksanakan sesuatu yang telah disepakati keduanya, dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan: Nafadh al-aqdi.
2). Sesuatu yang terdiri dari dua kehendak baik berupa ucapan atau yang lain, dan menetapkan adanya iltizam (Al-Sanhuri, 1970: 34).
Istilah iltizam dalam pembahasan akad ini adalah suatu hubungan antara dua pihak menyangkut hak dan kewajiban (Al-Siddiqi, 1976: 39), dalam hal ini dapat berupa keharusan melakukan suatu atau tidak melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan orang lain. Misalnya, mengganti barang yang telah dirusakkan oleh peminjam, atau tidak menggunakan barang titipan tanpa adanya kerelaan dari penitip.
Adapun iltizam yang ditimbulkan oleh akad antara dua pihak ada dua macam yaitu, pertama: Iltizam-iltizam yang dengan sendirinya harus dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad tanpa adanya persyaratan yang tegas, seperti pembeli menyerahkan barang, mengganti barang atau kerugian pada barang-barang yang ada cacatnya. Penjual menyerahkan harga. Dalam akad sewa- menyewa, maka penyewa diharuskan membayar harga sewa, pemilik barang harus menyerahkan barang sewaannya kepada penyewa. Keharusan-keharusan (iltizam-iltizam) tersebut harus ditegakkan, supaya maksud dan tujuan (natijah) akad dapat tercapai.
Kedua: Iltizam-iltizam yang lain yang ditimbulkan oleh akad, tetapi tidak harus dipenuhi oleh salah satu pihak, kecuali disyaratkan oleh pihak kedua di dalam akad, misalnya, pembeli mensyaratkan supaya barang yang dibelinya itu diantar sampai rumah. Atau penjual mensyaratkan bahwa ketika terdapat cacat pada barang- barang yang dijualnya tidak menjadi tanggung – jawab penjual. Atau dalam akad istishna’ (pesanan), pemesan mensyaratkan pembayaran harga barang pesanannya dilakukan dengan cara diangsur (kredit). Bentuk iltizam-iltizam tersebut tidak dapat berlaku dengan sendirinya pada saat akad itu ada, akan tetapi harus diperjanjikan terlebih dahulu saat terjadinya akad. Karena prinsip dasar yang harus ditegakkan didalam suatu perjanjian adalah menghargai kehendak (ihtiram al-iradah) diantara para pihak yang melakukan perjanjian, tanpa dengan prinsip tersebut, maka natijah diadakannya akad tidak akan terpenuhi yaitu berupa maksud dan tujuan serta akibat diadakannya perjanjian (akad) (Ibn Qudamah, 1967: 562-569).
Atas dasar itu, maka para fuqaha menetapkan suatu prinsip bahwa pada dasarnya akad itu memiliki sifat luzum (mengikat) artinya, tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak yang mengadakan perjanjian melakukan atau mencabut kembali terhadap kesepakatan yang telah diperjanjikannya, tanpa dengan persetujuan pihak lain, kecuali karena terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh Syara’. Alasan-alasan tersebut antara lain:
a). Halat al-Fasakh artinya bahwa akad yang fasid atau rusak memberi hak kepada masing-masing pihak yang melakukan akad, bahkan hakim sekalipun dapat menfasakhkan akad selama Syara’ tidak melarangnya. Misalnya upah terhadap pembunuh, akad nikah antara laki-laki dengan laki- laki (nikah sejenis).
b). Halat al-Ikrah artinya bahwa akad-akad yang dilakukan dengan cara paksaan, memberi hak kepada orang yang dipaksa melakukan akad tersebut untuk menfasakhkan akad atau meneruskannya, sebagaimana akad nikah seorang gadis yang dipaksa oleh walinya.
c). Halat al-Khiyarat artinya bahwa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi salah satu pihak yang melakukan akad (transaksi) serta untuk memelihara hak-haknya, maka salah satu pihak dapat membatalkan akadnya karena adanya cacat pada barang yang menjadi obyek akad antara lain berupa: Khilabah yang meliputi: khiyanat, tanajus, taghrir dan tadlis al-‘aibi
c. Transaksi (Akad) dalam Perikatan Hukum Umum.
Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, akad (perjanjian) didefinisikan sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. (Gunawan, 2004: 92).
Pengertian perjanjian diatas mengandung rumusan bahwa adanya perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain dengan konsekuensi hukum bahwa satu pihak harus melaksanakan prestasi (sesuatu yang harus dilakukan) terhadap pihak lain (sebagai pihak yang menerima prestasi). (Soebekti, 1978: 12). Selanjutnya berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar supaya perjanjian itu sah dan mengikat. Syarat-syarat tersebut antara lain:
a). Adanya kesepakatan diantara pihak yang mengikatkan diri.
b). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c). Suatu pokok persoalan tertentu
d). Suatu sebab yang tidak terlarang.
Keempat unsur diatas dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan menjadi: Unsur subyektif dan unsur obyektif.
Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian.
Unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan daripada obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan itu, harus sesuatu yang tidak dilarang atau tidak diperkenankan oleh hukum. Sehingga apabila tidak terpenuhinya salah satu dari empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian.
Menurut teori hukum perikatan, bahwa kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak bebas dari dua pihak atau lebih mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, sehingga kesepakatan bebas tersebut merupakan prinsip yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: ” Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan” (Gunawan, 2004: 95).
Konsep-konsep yang dikemukakan baik oleh para ahli hukum Islam maupun ahli hukum perdata Indonesia terkait dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, secara substansi tidak terdapat perbedaan antara keduanya, termasuk masalah yang menyangkut prinsip mengenai saat tercapainya kesepakatan, maka lahirlah suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum mengikat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Misalnya dalam perjanjian konsensual, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, setelah terjadi kesepakatan, maka lahir perjanjia, pada saat yang bersamaan, juga menerbitkan perikatan antara kedua pihak yang telah bersepakat dan berjanji. Dengan lahirnya perikatan diantara dua pihak yang bersepakat, masing-masing pihak harus melaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan (wanprestasi), pihak lain berhak menuntut ganti rugi. (Gunawan, 2004: 97). Teori hukum perjanjian tersebut, oleh para ahli hukum Islam (fuqaha) diberi istilah dengan nama akad lazim.
Sumber: Mujibatun. 2013. Himpunan Hadis-Hadis Transaksi Perspektif Etik. Rafi Sarana Perkasa. Semarang
WA penulis : 0817229135






