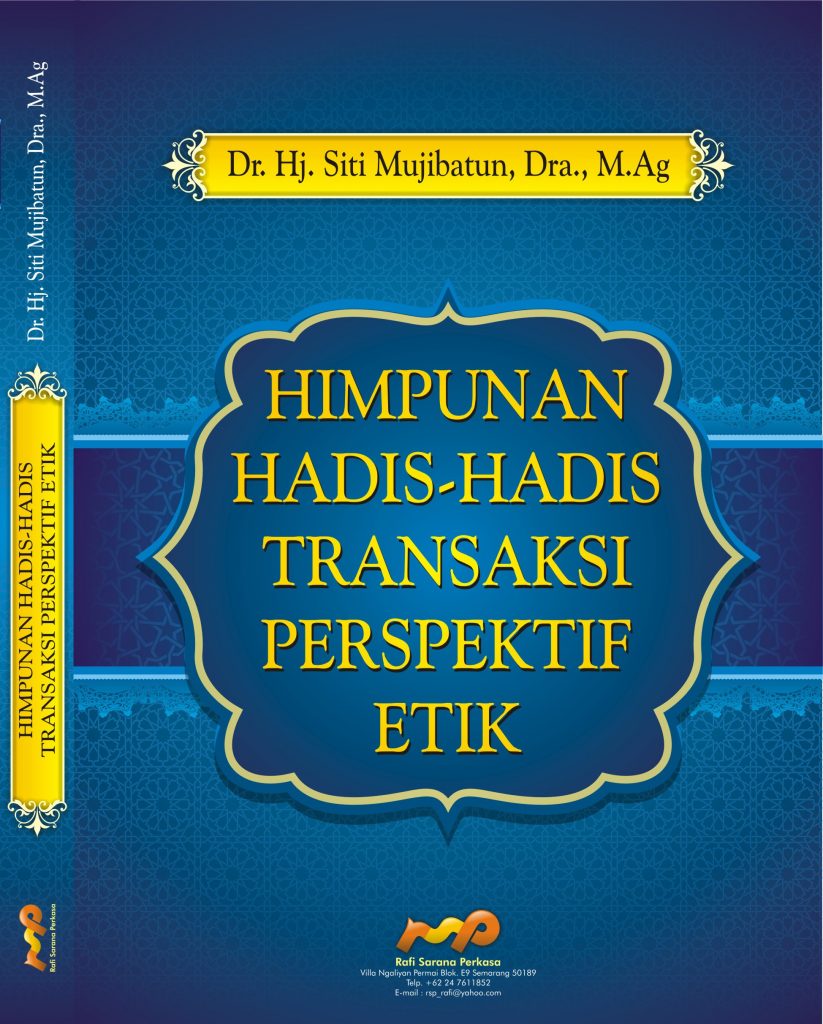
https://hardiwinoto.com/landasan-hukum-transaksi/
https://hardiwinoto.com/transaksi-dalam-perspektif-fiqh-muamalah/
Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan yang lalu yaitu tentang definisi akad, uraian ini akan menyinggung tentang prinsip-prinsip dalam nadhariyah al-‘uqud (teori akad) menurut para fuqaha, yang menjelaskan adanya hubungan akad dengan bentuk – bentuk tasharruf yang dilakukan oleh manusia.
Adapun yang dimaksud dengan tasharruf menurut ahli fiqh adalah: Segala sesuatu yang terbit dari seseorang atas dasar kehendaknya dan Syara’ menetapkan terhadapnya beberapa natijah hak (Madhkur, 1967: 367).[1]
Misalnya: Usaha seseorang yang dilakukan dengan tenaga badan, seperti mengusahakan untuk memiliki benda-benda yang mubah yang belum menjadi milik orang lain (ihraz al-Mubahah) disebut : tasharruf fi’li. Atau dengan menyatakan kepada orang lain untuk memberikan benda dengan meminta imbalan harga (penjual) yang kemudian disetujui oleh pihak lain (pembeli) atau yang lazim disebut dengan akad bai’. Akad bai’ inilah menurut para fuqaha termasuk dalam tasharruf qauli ‘aqdi (Al-Siddiqi, 1976: 132).
Dalam pembahasan mengenai prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam mewujudkan akad, para fuqaha menetapkan beberapa prinsip sebagai berikut:
1. Prinsip Prosedural dan Substansial.
Prinsip prosedural adalah bahwa setiap perbuatan para mukallaf dapat dinilai atas dasar bentuk dan cara-cara yang nampak sesuai dengan bentuk yang dilakukan tanpa mempertimbangkan apa yang dikehendaki sebenarnya dari pelaku tersebut.
Prinsip substansial adalah bahwa setiap perbuatan para mukallaf dinilai dari maksud dan tujuan (niat) dari pelaku sekalipun secara kenyataan berlainan. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewa, suatu perjanjian dengan suatu pembayaran balas jasa dari pihak penyewa, yang bisa juga disebut perjanjian i’arah (pinjam meminjam). Maka apabila dua orang mengadakan persetujuan dengan pernyataan i’arah, akan tetapi dengan syarat bahwa pihak peminjam memberikan pembayaran jasa kepada pihak yang meminjamkan (pemilik barang), maka persetujuan ini harus dianggap sebagai perjanjian sewa menyewa, bukan pinjam meminjam menurut ucapan yang dinyatakan.
Contoh lain: Seorang anak menerima hibah sebidang tanah dari orang tuanya dengan menggunakan akad jual beli diatas kwitansi yang dibubuhi dengan tanda tangan dari masing – masing (orang tua dan anak). Secara Syar’i, akad tersebut tetap disebut hibah (suatu pemberian), bukan akad jual beli meskipun dengan dasar bukti kwitansi. Oleh sebab itu maka para fuqaha menetapkan beberapa prinsip yang perlu dipegangi guna merealisasikan jiwa Syari’at dalam upaya membina hukum, dalam menegakkan prinsip -prinsip universal ajaran Islam antara lain menegakkan hak, keadilan, kesamaan, persaudaraan, maupun dalam memelihara maslahat (kebaikan), menolak mafsadat (kerusakan) dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi.
Adapun kaedah – kaedah yang dijadikan sebagai pegangan baik yang menyangkut bidang ibadah mahdhah (yang langsung berhubungan dengan Allah) maupun dalam bidang (muamalah) transaksi antar manusia di bidang hak-hak dan kebendaan antara lain :
ا لاؤمور بمقا صدها .
Artinya : “Semua perkara bergantung pada maksud (tujuan) nya.” (Khalaf, 1976: 21).
Atas dasar pada prinsip diatas, dalam bidang muamalah yang terkait dengan tindakan – tindakan yang berhubungan dengan kesepakatan dengan pihak lain, semua hukumnya didasarkan pada maksud dan tujuan daripada perjanjian yang dibuatnya. Hal ini berdasar pada hadis Nabi saw :
انما الاءعمال بالنيات وانما لكل اءمرئ مانوي
Artinya: “Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niat dan sesungguhnya setiap orang itu menurut apa yang diniatkan. (H.R. Bukhari, 1978: 3 ).
Maksud dari pada hadis diatas adalah, bahwa semua perbuatan didasarkan pada maksud dan tujuan, yaitu niat. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada setiap perkara adalah menurut apa yang menjadi maksud dan tujuan dari tindakan itu.
Apabila terjadi perbedaan antara niat dengan kenyataan, maka ketentuan hukum yang harus diambil adalah hukum menurut niat (maksud dan tujuan) jika hal itu dapat diketahui. Atas dasar ini, jika makna dari perkataan berbeda dari bentuk dan ucapannya, maka yang harus dianggap benar atau yang harus diambil adalah pengertian menurut makna yang sebenarnya, bukan menurut ucapannya.sebagaimana disebutkan dalam sebuah qaidah :
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للاْ لفاظ والمباني
Artinya: “Yang dihargai dalam bidang akad ialah makna dan maksud bukan ucapan dan perkataan.” (Al-Jauziyyah, 1317 H: 101).
Di dalam membatasi makna, misalnya dalam menentukan halal haramnya, sah batalnya suatu akad, harus dihubungkan dengan maksud dan tujuan (niat), bukan kepada ucapan. Oleh karenanya tidak sah berpegang pada harfiyah lafaz} (prosedural) jika terbukti bahwa niat (maksud dan tujuan) bukan sebagai yang diucapkan itu (Al-Jauziyah, 1317 H: 101).
Berdasar pada kaidah diatas, apabila bertentangan antara niat dengan ucapan, harus didasarkan pada niat jika mungkin diketahui niat itu. Akan tetapi jika antara maksud/ tujuan berbeda dengan ucapan tersebut berkaitan dengan kepentingan pihak lain (ketiga), sedangkan niat itu sulit diketahui, maka para fuqaha menggunakan ucapan dalam menentukan hukum bukan berdasar pada niat. Hal ini mendasarkan pada sebuah hadis :
نحن نحكم بالظواهر والله يتولي علي السرائر
Artinya: “Kami (Nabi) memutuskan perkara berdasarkan pada kenyataan, dan Allah yang menguasai batin manusia.”.( Al-Amidi, 1347 H: 91 ).
Para fuqaha dikala memegangi kenyataan yang dhahir, mendasarkan pada alasan dharurat dan atas dasar pengecualian, sekaligus dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentingan orang lain. (Mah}mas}ani, 1949: 468).
Sebagai contoh: Seseorang bersumpah dihadapan hakim yang menyuruh dia bersumpah, maka ucapannyalah yang harus dipegang, yakni berdasar niat hakim atau niat dari orang yang meminta sumpah, bukan niat yang mengucap sumpah sendiri, hal ini mengingat hadis Nabi saw.
اليمين علي نية المستحلف
Artinya: “Sumpah adalah menurut niat orang yang menyuruh bersumpah.” (Mahmasani, 1949: 468 ).
Atas dasar hadis tersebut, maka di dalam bersumpah, seseorang tidak boleh menyembunyikan penafsiran yang berlainan dengan makna ucapan sumpah itu, meskipun ada pendapat dari sebagian ulama membolehkan menyembunyikan makna sumpah yang di maksud, akan tetapi karena keadaan terpaksa, yaitu ketika orang yang bersumpah dalam keadaan teraniaya.[2]
Berdasarkan uraian diatas, pada prinsipnya hukum-hukum yang berpautan dengan perbuatan seseorang, dalam fiqh muamalah menganut prinsip substansial bukan prosedural, sehingga yang dapat dihukumi adalah berdasarkan pada maksud dan tujuan (niat) dari si pelaku, sejauh niat tersebut dapat dipahami. Akan tetapi jika terjadi pertentangan antara niat dengan kenyataan, maka harus diperhatikan niatnya, kecuali jika menurut kenyataan lahir terkait dengan hak-hak dan kepentingan orang lain (pihak ketiga), dalam hal ini kenyataan lahir yang harus diperhatikan, dengan alasan karena terpaksa dan sebagai hukum pengecualian.
2. Prinsip yang berhubungan dengan syakhshiyyah (pelaku transaksi).
a. Adanya sult}a>n al-Ira>dah
Yang dimaksud dengan sult}a>n al-Ira>dah adalah kemerdekaan kehendak si akid pada asal akad, pada natijah-natijahnya dan pada batas-batas kemerdekaannya, dalam arti bahwa sampai dimanakah Syara’ menghargai kekuasaan kehendak seseorang itu dengan kebebasan bergerak, bebas berkehendak dan bebas bertindak yang dalam hal ini terkait dengan empat (4) macam bentuk kebebasan si akid.
Pertama : Kebebasan dalam mengadakan transaksi (akad) dengan seseorang.
Kedua : Kebebasan mengadakan transaksi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak
Ketiga : Kebebasan dalam membuat berbagai bentuk perjanjian dalam transaksi menurut kehendak kedua belah pihak.
Keempat : Kebebasan dalam menentukan batasan-batasan dalam pelaksanaan transaksi, misalnya dengan mengajukan berbagai persyaratan yang mereka sepakati bersama. (Madhkur, 1965: 357).
b. Adanya Sifat Luzum.
Suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan kehendak yang bebas tanpa tekanan dari siapa pun memiliki sifat luzum artinya bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan akad, memiliki sifat mengikat antara mereka. Tidak boleh salah satu diantara para pihak membatalkan perjanjian yang telah disepakati tanpa persetujuan pihak lain. (Al-Siddiqi, 1976: 82). kecuali atas dasar alasan-alasan yang dibenarkan oleh Syara’.
Misalnya: Dalam transaksi (akad) jual beli, A membeli mobil milik B dengan harga Rp. 20.000.000; kemudian B menyetujuinya. Pembayaran uang dan penyerahan barang akan dilakukan satu (1) setelah adanya kesepakatan, dan B menyetujui. Akan tetapi pada saat pembayaran uang dan penyerahan barang akan dilakukan, B sebagai penjual membatalkan perjanjian yang telah disepakati, sedangkan A telah siap dengan sejumlah uang (Rp.20.000.000;) sebagai pembayaran terhadap mobil itu. Maka tindakan B sebagai penjual mobil yang membatalkan sepihak tanpa persetujuan A adalah termasuk sebuah pengingkaran terhadap janji yang telah disepakati keduanya.
Selain akad memiliki sifat luzum (mengikat pada pihak-pihak yang berakad dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya kecuali atas persetujuan pihak lain), bersifat ghairu lazim (tidak mengikat bagi pihak yang berakad, sehingga kapan saja dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak lain). Hal ini berlaku baik pada akad musamma maupun ghairu musamma.
3. Prinsip yang berhubungan dengan natijah akad (keputusan adanya akad).
Prinsip dasar yang harus ditegakkan didalam suatu perjanjian adalah menghargai kehendak (ih}tira>m al- ira>dah) diantara para pihak yang melakukan perjanjian, tanpa dengan prinsip tersebut, maka natijah diadakannya akad tidak akan terpenuhi yaitu berupa maksud dan tujuan serta akibat diadakannya sebuah perjanjian.
Dalam menghargai kehendak pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, perlu memperhatikan keinginan yang sebenarnya ketika mereka melakukan kesepakatan, misalnya, pembeli ingin membeli mobil dengan cat yang masih orisinil, akan tetapi penjual mobil tidak mengetahui bahwa sebenarnya mobil tersebut catnya sudah tidak orisinil (sudah dilakukan pengecatan ulang). Dalam hal ini, untuk mewujudkan ihtiram al-iradah (menghargai keinginan) pembeli mobil yang masih orisinil catnya tidak dapat terpenuhi, sehingga pembeli dapat membatalkan apa yang telah disepakatinya dengan penjual atas dasar ih}tira>m al-ira>dah (menghargai kehendak)dari pihak pembeli, dan penjualpun harus menerima pembatalan dari kesepakatan yang telah dibuatnya itu.
4. Prinsip yang berhubungan dengan terbentuknya akad.
Untuk menciptakan suatu perjanjian, harus mengandung unsur-unsur antara lain: a). Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. b). obyek (barang) yang diperjanjikan. c). shighah (ijab dan qabul) atau suatu ungkapan yang menunjukkan adanya kesepakatan[3], dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan rukun akad (sesuatu yang harus ada pada sebuah akad, tanpa itu maka akad tidak dapat terwujud).
Adapun untuk mewujudkan suatu perjanjian yang sah dalam perspektif fiqh muamalah, masing-masing dari ketiga unsur diatas harus memenuhi persyaratan yaitu :
Pertama: Bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus cakap bertindak (ahliyah).
Kedua:Bahwa obyek yang diperjanjikan harus memenuhi kriteria antara lain : (a).
diperbolehkan menurut Syara’, (b). Dapat diserahterimakan. (c). Bernilai
dan dimiliki oleh seseorang menurut
Syara’. [4]
Ketiga:
Shighah berupa ijab dan qabulyaitu
pernyataan kehendak masing-masing pihak, harus memenuhi syarat antara lain:
(a). Harus jelas pengertiannya. (b). Harus bersambung antara ijab (penawaran)
dengan qabul (penerimaan). (Al-Zarqa’, 1968: 313).
[1] Tasharruf menurut Salam Madhkur diartikan sebagai berikut:
كل ما يصدر من شخص باءرادته ويرتب عليه الشرع نتاءج حقوقبة.
Artinya: Segala sesuatu yang terbit dari seseorang atas dasar kehendaknya dan Syara’ menetapkan beberapa natijah hak.
[2] Di Dalam kitab Miftah al-Karamah fi madzahibi al-Syi’ah al-Imamiyah, Juz V, (Mesir: Dar ‘Ilmiyah, 1326 H), hal. 18 dikutip oleh Subhi Mahmasani dalam kitab al- Falsafah al- Tasyri’ al- Islami halaman 179 menjelaskan bahwa debitor yang sedang kesukaran boleh inkar dan bersumpah jika hawatir dengan pengakuannya itu dan menutup-nutupinya.
[3] Menurut mazhab Hanafi unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya akad atau dengan istilah fiqh disebut rukun hanya terdiri dari ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut mazhab selain Hanafi rukunakad ada 3 yaitu : Aqid (Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian), mahal (barang yang di perjanjikan), shighah (ungkapan yang menggambarkan adanya persetujuan). (Madhkur, ibid, 359).
[4] Di dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan mal al-mutaqawwam. Bandingkan dengan unsur-unsur yang harus ada pada perjanjian menurut Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Lihat Gunawan Wijaya, Perikatan Yang lahir dari Perjanjian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 93.
Judul:Himpunan Hadis-Hadis, Transaksi Perspektif Etik
ISBN: 978-602-18368-3-0
Penulis: Dr. Hj. Siti Mujibatun, Dra., M.Ag
Penerbit: Rafi Sarana Perkasa (RSP)






